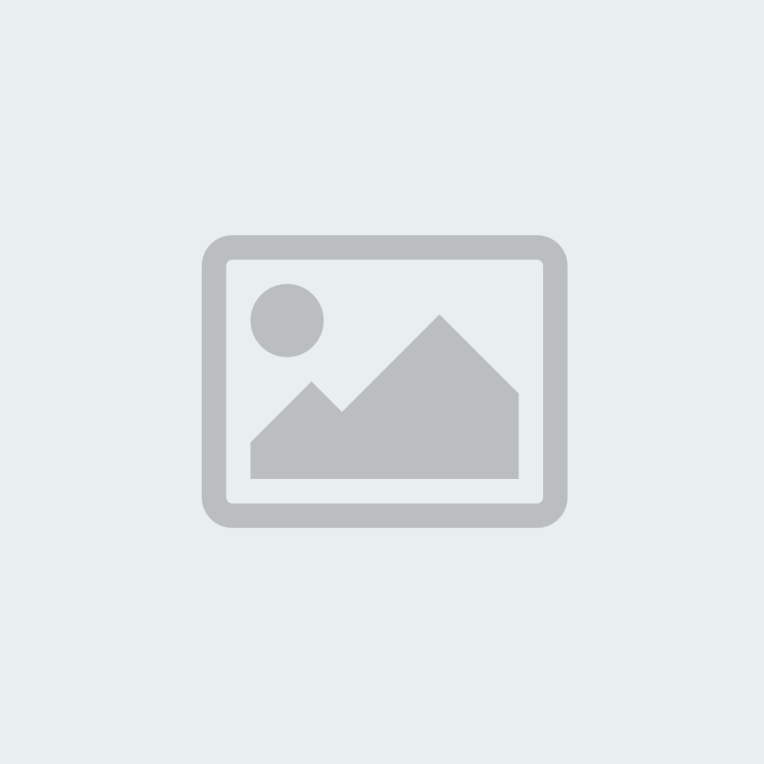
Admin
 ai
ai
 0 comment
0 comment
 30 Sep, 2025
30 Sep, 2025

Selama berabad-abad, manusia membangun pengetahuan lewat observasi, eksperimen, dan teori. Dari zaman filsuf Yunani sampai ke ilmuwan modern, cara kita memahami dunia selalu berkembang. Thomas Kuhn, seorang filsuf sains, menyebut setiap lompatan besar dalam ilmu pengetahuan sebagai “pergeseran paradigma” – sebuah perubahan cara pandang mendasar tentang bagaimana dunia bekerja.
Sekarang, kita masuk ke bab baru: era kecerdasan buatan (AI). Pertanyaannya, apakah AI sekadar alat bantu baru, atau ia sedang menggeser paradigma ilmu pengetahuan itu sendiri?
Kalau dulu pengetahuan dikumpulkan lewat observasi manual dan eksperimen laboratorium, kini AI bisa menganalisis data dalam jumlah super masif. Misalnya:
Dengan kecepatan dan akurasinya, AI seperti menjadi “ilmuwan asisten” yang bekerja 24/7.
Di sinilah pertanyaan menarik muncul. AI awalnya dianggap hanya alat – sama seperti mikroskop atau teleskop. Tapi ketika AI mulai menghasilkan hipotesis, membuat prediksi, bahkan menulis artikel ilmiah, muncul perdebatan:
Apakah AI hanya memperluas kemampuan kita, atau sudah menjadi aktor epistemik – pihak yang turut menciptakan pengetahuan?
Kalau iya, maka ini berarti kita sedang masuk ke paradigma baru, di mana pengetahuan tidak hanya berasal dari manusia, tapi juga dari entitas buatan.
Tentu saja, tidak semua berwarna emas. AI punya sisi gelap:
Bias data bisa membuat hasilnya menyesatkan.
Black box problem – kita sering tidak tahu bagaimana AI mengambil keputusan.
Etika – siapa yang bertanggung jawab kalau keputusan AI salah?
Artinya, meski AI menjanjikan, kita tetap perlu kehati-hatian dalam menganggapnya sebagai sumber pengetahuan.
Kalau Kuhn melihat sejarah, setiap paradigma lama runtuh karena anomali yang tidak bisa dijelaskan. AI mungkin sedang memainkan peran itu: memberi cara baru membaca realitas yang kadang berbeda dengan cara manusia memahaminya.
Apakah ini berarti kita sudah di era paradigma baru?
Mungkin belum sepenuhnya. Tapi jelas, AI bukan sekadar alat. Ia adalah katalis yang memaksa kita mendefinisikan ulang apa itu pengetahuan, siapa yang memproduksinya, dan bagaimana kita mempercayainya.
Sejak dulu, manusia percaya bahwa pengetahuan lahir dari akal budi, pengalaman, dan refleksi kritis. Kita melakukan observasi, lalu menarik kesimpulan. AI, sebaliknya, bekerja dengan cara berbeda: ia memproses miliaran data, menemukan pola, lalu menghasilkan prediksi—tanpa “kesadaran” atau “intuisi” seperti manusia.
Ini menimbulkan pertanyaan filosofis:
Yang jelas, AI membuat kita harus merenungkan ulang hubungan manusia dengan pengetahuan. Alih-alih menggantikan manusia, mungkin AI adalah “cermin besar” yang memperlihatkan bagaimana kita sendiri membangun ilmu. Dari situ, kita bisa belajar, mengkritisi, dan memperbaiki cara kita memahami dunia.
Maka, era AI bukan sekadar soal teknologi. Ia adalah undangan bagi kita untuk menulis ulang paradigma pengetahuan, di mana manusia dan mesin berjalan bersama mencari kebenaran.
Admin
0 comment